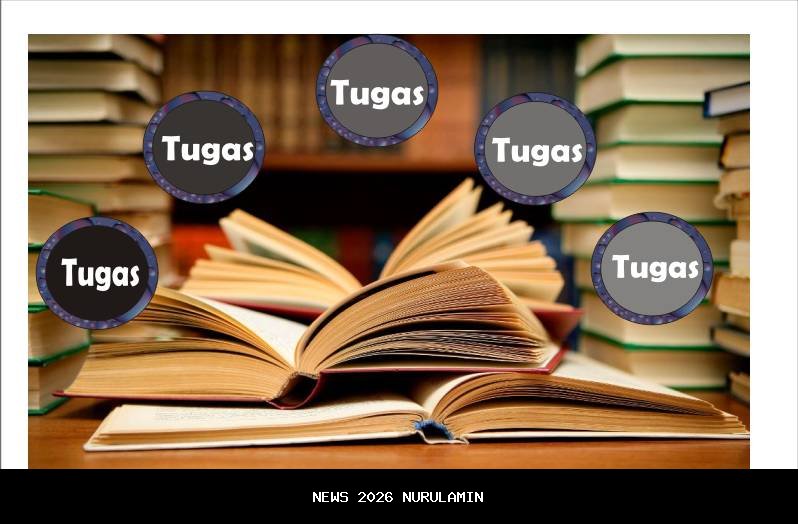
Makassar Kota Inklusi: Dari Wacana ke Praktik Ruang
Makassar kini semakin dikenal sebagai kota yang berkomitmen pada inklusi. Narasi ini muncul dalam berbagai forum resmi pemerintah, seperti pidato wali kota, agenda peringatan hari-hari disabilitas, dan dokumen perencanaan pembangunan. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa penyandang disabilitas harus menjadi bagian penting dalam pembangunan kota.
Di tingkat masyarakat, kelompok penyandang disabilitas terus berupaya memperluas partisipasi, memperkuat hak, serta meningkatkan kebijakan melalui audiensi, advokasi, dan inisiatif publik. Kombinasi antara dorongan warga dan respons pemerintah membentuk wajah "Makassar Kota Inklusi" saat ini.
Wacana Inklusi dalam Teori Produksi Ruang
Dalam teori produksi ruang dari Henri Lefebvre (1991), fase awal inklusi berada pada level representations of space ruang konseptual yang diproduksi melalui media politik, dokumen perencanaan, dan pengakuan simbolik negara atas tuntutan warga. Narasi inklusi bahkan dilembagakan secara resmi melalui RPJMD Kota Makassar 2025-2029 dengan visi Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan.
Namun, visi ini belum diturunkan ke dalam desain kebijakan. Disabilitas hadir kuat sebagai visi, tetapi menghilang dalam struktur program prioritas daerah. Masalah ini diperkuat oleh kerangka regulasi yang masih tertinggal. Hingga kini, Kota Makassar masih menggunakan Perda Kota Makassar 6/2013 yang bertumpu pada pendekatan medical-charity.
Penyandang disabilitas diposisikan sebagai objek belas kasihan dan penerima bantuan sosial. Perda ini belum sejalan dengan paradigma berbasis hak sebagaimana ditekankan dalam UU 8/2016 yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum dan warga negara dengan hak setara atas aksesibilitas dan partisipasi politik.
Kontradiksi antara Wacana dan Regulasi
Kontradiksi antara wacana dan regulasi menjadi jelas ketika ditarik ke level spatial practice, yakni ruang yang diproduksi melalui anggaran, infrastruktur, dan layanan publik. Dalam APBD Kota Makassar Tahun 2025, tidak ditemukan satu pun pos anggaran yang secara eksplisit dialokasikan untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Tidak ada Unit Layanan Disabilitas (ULD) pendidikan, tidak ada kewajiban belanja aksesibilitas dalam proyek infrastruktur, tidak terdapat afirmasi pasar kerja bagi difabel, serta tidak ada klaster rehabilitasi berbasis hak. Dengan kapasitas fiskal Makassar yang mencapai triliunan rupiah, ketiadaan ini bukan sekadar persoalan teknis. Ia adalah keputusan politik anggaran tentang siapa yang dianggap layak diproduksi dalam ruang kota.
Ketika estetika kota, kawasan bisnis, dan proyek properti terus dibiayai, sementara aksesibilitas dan layanan difabel absen, negara kota sedang memproduksi ruang yang secara sistematis menyisihkan tubuh difabel dari pusat kehidupan kota.
Perbandingan dengan Surakarta
Situasi ini menjadi sangat kontras jika dibandingkan dengan Surakarta, yang dengan kapasitas fiskal lebih kecil justru membentuk dan membiayai UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif, sekaligus mengintegrasikan isu disabilitas dalam sektor sosial, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Di Surakarta, inklusi tidak berhenti sebagai wacana, tetapi diproduksi sebagai sistem kebijakan dan anggaran.
Ketiadaan struktur kebijakan dan anggaran ini berdampak langsung pada space of representation, yakni ruang yang benar-benar dihidupi penyandang disabilitas. Di level ini, kota tidak dibaca melalui pidato dan dokumen, melainkan melalui akses bergerak, bekerja, bersekolah, dan berpartisipasi.
Bagi banyak difabel di Makassar, kota masih dihidupi sebagai ruang hambatan: trotoar tidak aksesibel, transportasi publik belum ramah kursi roda, sekolah inklusif terbatas, serta pasar kerja yang belum membuka ruang setara.
Revisi Perda dan Keberanian APBD 2026
Agar Makassar tidak terus terjebak pada inklusivitas simbolik, ada tiga medan kebijakan yang harus diperebutkan pada 2026. Pertama, revisi Perda Disabilitas. Perda 6/2013 perlu diganti dengan regulasi baru yang sepenuhnya berbasis UU 8/2016, dengan mengubah paradigma dari charity menuju hak.
Revisi ini tidak akan bergerak tanpa inisiatif DPRD dan tekanan berkelanjutan komunitas disabilitas, karena perubahan paradigma berarti juga perubahan beban kewajiban negara. Kedua, alokasi khusus disabilitas dalam APBD 2026 yang terukur dan eksplisit. Di titik ini, tanggung jawab tidak lagi abstrak.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD menjadi aktor kunci. ULD pendidikan inklusif, belanja aksesibilitas universal di sektor pekerjaan umum dan perhubungan, afirmasi ketenagakerjaan difabel, serta penguatan layanan rehabilitasi sosial dan kesehatan berbasis hak harus muncul sebagai baris anggaran yang bisa diaudit publik, bukan sekadar niat baik.
Ketiga, integrasi lintas SKPD, yang menempatkan disabilitas bukan hanya sebagai urusan dinas sosial. Di titik ini, peran Wali Kota sebagai koordinator utama birokrasi menjadi krusial. Tanpa perintah politik yang tegas, pendidikan, kesehatan, perhubungan, ketenagakerjaan, dan infrastruktur akan terus bekerja sektoral, sementara hak difabel tetap terfragmentasi.
Jika langkah-langkah ini tidak segera diperebutkan secara politik, maka Makassar Kota Inklusi berisiko besar berhenti sebagai representations of space yang indah dalam wacana. Sementara dalam spatial practice dan ruang hidup harian, penyandang disabilitas tetap berhadapan dengan kota yang ramah bagi estetika dan investasi, tetapi belum ramah bagi keberagaman tubuh warganya.










Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar